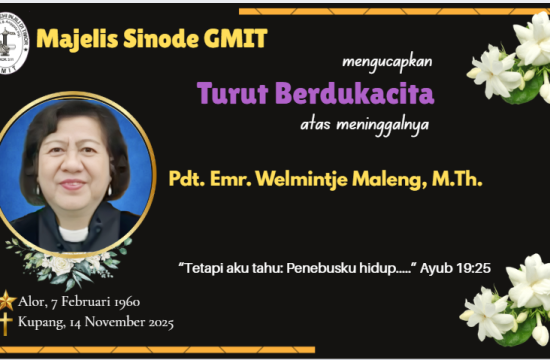Abstrak
Artikel ini mengkaji kontribusi iman Kristen terhadap kesejahteraan manusia (human flourishing) tanpa jatuh ke dalam teologi kemakmuran atau individualisme kapitalis. Melalui refleksi terhadap artikel ‘Human Flourishing: Exploring Protestant Goods in Changing Contexts’ (Reformed World, Vol. 59 No. 3, 2009), tulisan ini menyoroti bagaimana gereja, khususnya GMIT, dapat memahami panggilannya dalam konteks kemiskinan. Analisis ini diperkaya dengan pemikiran Raymond Fung tentang teologi dari pinggiran dan pendekatan Gerald West yang menggabungkan teologi publik dan teologi akar rumput. Dengan demikian, teologi flourishing dipahami bukan sebagai pencapaian material, melainkan sebagai praksis shalom: hidup bersama yang adil, berkelanjutan, dan berbelas kasih.
Pendahuluan
Kesejahteraan manusia merupakan tema universal yang selalu menjadi pergumulan teologis di tengah dunia modern. Dalam arus kapitalisme global dan teologi kemakmuran yang menjanjikan berkat material sebagai bukti iman, teologi Reformed menawarkan jalan berbeda. Ia mengajak umat beriman menafsirkan kesejahteraan bukan sekadar sebagai kenikmatan pribadi, melainkan sebagai partisipasi dalam karya Allah menghadirkan shalom. Edisi Reformed World Vol. 59 No. 3 (Desember 2009) mengangkat tema ‘Human Flourishing: Exploring Protestant Goods in Changing Contexts’ untuk menegaskan bahwa iman Kristen harus menjadi kekuatan transformatif bagi kesejahteraan manusia tanpa kehilangan kepekaan terhadap penderitaan dan kemiskinan. Tulisan ini berupaya mengelaborasi gagasan tersebut dalam konteks Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT), yang berhadapan langsung dengan realitas kemiskinan struktural.
- Human Flourishing sebagai Shalom
Konsep ‘human flourishing’ sering disalahpahami sebagai kesuksesan individu yang diukur lewat kekayaan, kesehatan, dan kebahagiaan pribadi. Namun, para teolog dalam Reformed World menegaskan bahwa flourishing sejati berarti hidup dalam shalom Allah, keutuhan relasi antara Allah, sesama, dan ciptaan. Shalom bukan kondisi statis, tetapi proses rekonsiliasi yang berkelanjutan. Teologi ini menolak dua penyimpangan besar : pertama, teologi kemakmuran yang mengidentikkan iman dengan kekayaan; kedua, individualisme kapitalis yang meniadakan tanggung jawab sosial. Iman Kristen memanggil manusia untuk hidup dalam kasih dan tanggung jawab terhadap sesama. Flourishing tidak dapat dicapai sendiri; ia tumbuh dalam komunitas yang saling menopang. Itulah sebabnya gereja dipanggil menjadi ruang solidaritas dan pembelajaran bagi kehidupan bersama yang berkeadilan.
2. Teologi Salib dan Kerentanan Manusia
Reformed World menegaskan bahwa setiap teologi flourishing harus melewati ujian salib. Jika sebuah teologi mengabaikan penderitaan dan kemiskinan, ia kehilangan dasar Injil. Kristus yang tersalib mengajarkan bahwa kemuliaan manusia justru ditemukan dalam solidaritas dengan yang menderita. Dengan demikian, flourishing tidak berarti hidup tanpa kesulitan, tetapi kemampuan menemukan kasih dan makna di tengah penderitaan. Pandangan ini menolak paradigma modern yang menuhankan kesuksesan. Sebaliknya, ia mengajarkan bahwa kerentanan adalah bagian hakiki dari kemanusiaan. Dalam konteks gereja, penderitaan bukan tanda kutuk, melainkan kesempatan untuk menyalurkan kasih Allah kepada dunia.
3. Raymond Fung dan Teologi dari Pinggiran
Raymond Fung, seorang teolog metodis dari Asia, memperkenalkan konsep ‘sinned-againstness’ untuk menjelaskan dimensi dosa struktural yang dialami oleh kaum miskin dan tertindas. Ia menegaskan bahwa gereja tidak cukup hanya berkhotbah kepada orang miskin, tetapi harus berjuang bersama mereka. Bagi Fung, misi gereja adalah ‘mission with the poor’, bukan ‘mission for the poor’. Dalam solidaritas itulah manusia mengalami pemulihan martabat dan harapan. Pemikiran Fung membantu gereja memahami bahwa flourishing bukan hasil moralitas individu, melainkan proses sosial dan spiritual yang melibatkan transformasi struktur. Kesejahteraan sejati tidak dapat dipisahkan dari keadilan sosial dan pembebasan ekonomi.
4. Teologi Publik dan Teologi Akar Rumput
Gerald West dari Afrika Selatan mengembangkan pendekatan ‘Contextual Bible Study’ (CBS) yang mempertemukan teologi publik dan teologi akar rumput. Ia membaca Alkitab bersama masyarakat miskin, korban kekerasan, dan kelompok marjinal, agar suara mereka menjadi bagian dari teologi publik. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa teologi sejati lahir dari pergumulan nyata umat, bukan dari menara gading akademik. Model West sejalan dengan semangat Reformed World yang menekankan teologi dari pinggiran. Gereja tidak lagi berbicara atas nama rakyat, melainkan bersama rakyat. Dengan cara ini, teologi menjadi praksis partisipatif yang membentuk keadilan dan solidaritas.
5. Konteks GMIT: Iman di Tengah Kemiskinan
Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) berakar di tengah realitas kemiskinan, ketimpangan ekonomi, dan keterbatasan sumber daya, stunting, kemiskinan ekstrim, kurnagnya fasilitas pendidikan dan kesehatan. Dalam konteks ini, teologi flourishing bukan wacana abstrak, tetapi panggilan nyata untuk memulihkan kehidupan jemaat. GMIT telah mengembangkan berbagai inisiatif seperti koperasi jemaat, pertanian lestari, pelatihan UMKM, dan gerakan ‘Cinta Produk Jemaat’ sebagai ekspresi iman yang bekerja melalui kasih. Pemberdayaan ekonomi jemaat bukan sekadar strategi pembangunan, tetapi wujud pelayanan holistik. Dalam visi ini, shalom diterjemahkan menjadi kesejahteraan yang berkeadilan, ekologi yang terpelihara, dan pendidikan yang membebaskan. Teologi flourishing dalam GMIT menekankan keutuhan manusia rohani, sosial, dan ekonomi.
6. Etika Reformed dan Praksis Gereja
Tradisi Reformed menekankan bahwa kerja adalah panggilan ilahi. Manusia bekerja bukan untuk menimbun kekayaan, tetapi untuk melayani sesama. Kekayaan dipahami sebagai sarana untuk menegakkan keadilan sosial. Sejalan dengan 1 Timotius 6:17–19, orang kaya dipanggil untuk berbagi dan menaruh harapan pada Allah, bukan pada harta. Dalam praksis GMIT, etika kerja Reformed ini diterjemahkan menjadi spiritualitas tanggung jawab: bekerja dengan jujur, mengelola sumber daya secara berkelanjutan, dan memperjuangkan hak-hak masyarakat kecil. Dengan demikian, iman menjadi kekuatan produktif yang menciptakan ruang bagi kesejahteraan bersama.
Kesimpulan
Iman Kristen berkontribusi pada kesejahteraan manusia bukan dengan menjanjikan kekayaan, melainkan dengan mengajarkan solidaritas, keadilan, dan kasih. Teologi flourishing menegaskan bahwa hidup beriman berarti hidup dalam relasi yang benar dengan Allah dan sesama. Dalam konteks GMIT, hal ini berarti memperjuangkan keadilan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan sebagai wujud iman yang hidup. Sebagaimana ditegaskan Raymond Fung dan Gerald West, gereja yang setia bukanlah gereja yang kuat secara ekonomi, melainkan gereja yang hadir di antara yang lemah. Flourishing sejati bukan kemakmuran pribadi, tetapi kehidupan bersama yang memuliakan Allah melalui kasih, kerja, dan solidaritas. Inilah panggilan GMIT untuk menjadi tanda shalom di dunia yang terluka. ***