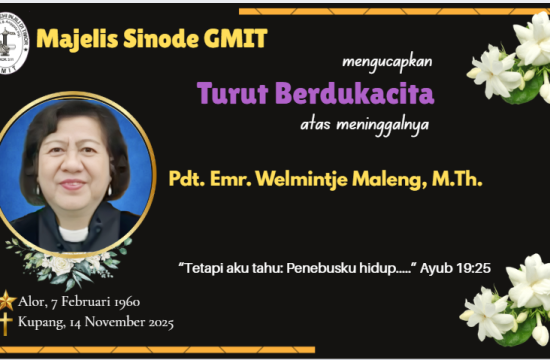Menurut Studi Penilaian Risiko Kesehatan Lingkungan (Enviromental Health Risk Assessment/EHRA) yang dilakukan pemerintah Kota Kupang, sampah adalah salah satu masalah ekologis utama di Kota Kupang. Sampah plastik yang berserakan di mana-mana, mencemari tanah dan air. Jika tidak dibakar (yang sebenarnya memperburuk masalah ekologis), sampah itu dibiarkan menumpuk tanpa pemilahan menghasilkan gas metana yang menyumbang emisi karbon. Di musim hujan ini, sampah plastik itu akan dibawa air hujan melalui sungai dan aliran air lainnya ke laut. Laut tercemar, ekosistem laut terganggu, dan semua makhluk yang bergantung pada laut ikut menanggung akibat buruknya. Persoalan yang sama ini juga terjadi di banyak tempat lain dalam wilayah pelayanan GMIT.
Selain tata kelola sampah yang belum maksimal serta kurangnya kesadaran masyarakat untuk memilah dan membuang sampah pada tempatnya, penggunaan bahan-bahan plastik yang kemudian menjadi sampah adalah faktor penyebab. Kampanye reuse, recycle, reduce ditambah dengan replacepunseolah tidak berpengaruh. Narasi “praktis” rupanya lebih berpengaruh. “Untuk apa ribet kalau ada yang praktis?” Ujungnya adalah konsumsi air kemasan dan plastik kresek menjadi pilihan utama. Sayang sekali, pertanyaan semacam itu dan tindakan yang mengikutinya juga dijumpai di dalam kegiatan gerejawi.
Karena itu, dengan berefleksi tentang pikul salib dalam konteks krisis ekologis, tulisan sederhana ini akan menunjukkan bahwa narasi “praktis” tersebut tidak selamanya benar. Bahkan, bagi para pengikut Kristus, “ribet” adalah bagian dari identitas iman.
Mengikut Yesus dalam konteks Krisis Ekologis
Salah satu kritik klasik kepada Kekristenan adalah bahwa iman ini terlalu fokus kepada manusia dan keselamatannya sampai mengabaikan ciptaan lain. Skema penciptaan – kejatuhan dalam dosa – penebusan yang dijadikan inti pemberitaan Kristen menempatkan manusia sebagai fokus, sebab hanya manusia yang jatuh dalam dosa.[1] Mungkin saja, skema itu tidak mengabaikan ciptaan lain sama sekali. Tetapi, kalau pun ciptaan lain diingat di situ, mereka berada di tempat ke dua. Alhasil, jika karya Allah itu harus diringkas, manusia lah yang dirujuk sebagai fokus. Selain itu, masalah lain yang ditimbulkan skema yang antroposentrik ini adalah dosa seolah-olah menjadi sentral dalam karya Allah. Seolah-olah karya Allah bagi ciptaan-Nya hanyalah untuk mengurus masalah dosa manusia.
Padahal, karya Allah itu lebih luas dari sekadar urusan dosa manusia. Kisah Allah dengan ciptaan-Nya adalah kisah kasih-Nya. Karena kasih-Nya Ia menciptakan, membuka ruang bagi ciptaan dalam relasi kasih Bapa, Anak dan Roh Kudus, atau yang disebut creatio ex amore Dei. Dalam kasih-Nya, Ia memelihara setiap ciptaan-Nya, dan membaharui seluruh ciptaan-Nya dalam karya Roh Kudus (Mzm. 104). Karena kasih-Nya yang begitu besar bagi dunia ciptaan-Nya, Kristus datang ke dunia (Yoh. 3:16). Allah menjadi bagian yang utuh dari dunia ini dengan menjadi manusia (Yoh. 1:14). Manusia di situ berasal dari kata Yunani sarx yang artinya juga mencakup seluruh ranah dunia materi, sebagaimana ditekankan Niel H. Gregersen dalam konsep Deep Incarnation-nya.[2] Dalam kemanusiaan Yesus, Allah menjadi bagian tak terpisahkan dari dunia ini, bersama dengan seluruh ciptaan oleh karena kasih-Nya. Dalam kasih Allah itulah penebusan terhadap dosa manusia diletakkan.
Paulus kemudian memahami bahwa dalam karya kasih Allah yang luas itu lah, Allah mendamaikan segala sesuatu (Yun. ta panta) baik yang ada di bumi maupun surga dengan diri-Nya melalui darah salib Kristus (Kol. 1:20). Dengan karya kasih itu, Allah membuat seluruh ciptaan (cosmos) mengalami dan menikmati relasi kasih dengan-Nya. Terumbu karang dan semak belukar, semut dan paus biru, dll. – semuanya berada bersama-sama dalam persekutuan kasih dengan-Nya.
Jika demikian karya Allah di dalam Kristus, para pengikut Kristus seharusnya hidup dalam relasi kasih Allah yang memberi dan membarui kehidupan seluruh ciptaan. Dosa memang merusak relasi manusia dengan Allah dan ciptaan-Nya. Ekspresi dosa itu merusak alam. Maka, dalam kasih Allah yang menaklukkan dosa, manusia seharusnya tidak lagi hidup dalam kuasa yang merusak. Mereka hidup dalam kasih yang menghidupkan bagi dan bersama ciptaan lain. Menjadi pengikut Yesus, berarti menjadi manusia baru yang hidup dalam kasih Allah bagi seluruh ciptaan. Sebab, tidak ada lagi kuasa yang bisa menghambat kasih dan ekpresinya yang menghidupkan.
Namun, mengikut Yesus seperti itu bukanlah perkara mudah. Itulah sebabnya, Yesus memberi tahu kita bahwa untuk mengikut-Nya, kita harus menyangkal diri dan pikul salib (Mat. 16:24; Mrk. 8:34; Luk. 9:23). Kedua hal itu tentu bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan. Hanya orang yang bisa menyangkal diri yang bisa memikul salib. Tetapi, yang jelas, keduanya juga bukanlah hal praktis. Dalam kesempatan ini, saya hanya secara spesifik membahas pikul salib.
Pikul Salib itu Tidak Praktis
Salib itu kayu kasar yang berat. Seseorang harus memikulnya di punggung, bukan hanya menggantung di leher atau memegang dengan satu tangan, apalagi dengan jari kelingking seperti memegang gantungan kunci. Dalam pemahaman demikian, pikul salib itu bukan urusan praktis. Pikul salib itu membutuhkan tenaga, serta strategi atau cara yang tepat. Jelas lah bahwa pikul salib itu “ribet.”
Dalam percakapan teologi, menjalani kehidupan sebagai murid Kristus dengan memikul salib itu dikenal dengan istilah cruciform. Secara sederhana cruciformadalah kehidupan yang berciri kerelaan untuk berkorban bahkan dengan harus menderita demi kebaikan bersama. Dalam konteks krisis ekologi, cruciformitu, menurut Sallie McFague, berarti menguasai diri, rela mengalami pengurangan, mematikan keinginan yang tak terbatas, serta mengendalikan kecenderungan egois yang merusak kehidupan seluruh ciptaan Allah.[3] Kasih adalah dasar kehidupan itu, sebagaimana yang ditunjukkan Kristus melalui pengurbanan-Nya. Jadi, cruciform itu berpusat pada Kristus dan karya-Nya.
Dalam teologi Kerajaan Allah, pikul salib itu bukan hanya soal akibat menentang kejahatan, tetapi juga melakukan kebenaran dan kebaikan sesuai karya Kristus. Dalam terang Injil Markus, kita melihat karya Kristus yang menentang kekuasaan politik yang menindas, tetapi Ia juga menunjukkan bagaimana seharusnya politik dijalankan dalam Kerajaan Allah. Markus 6:30-44 menceritakan kisah Yesus memberi makan orang banyak sebagai tindakan-Nya yang menentang sistem politik ekonomi Romawi yang mengeruk alam untuk kekayaan segelintir elit sambil membuat sebagian besar orang Galilea menderita.[4] Tetapi, Yesus juga menunjukkan bagaimana politik Kerajaan Allah terwujud, yaitu ketika makanan dari tanah dan Laut Galilea, lima roti dan dua ikan, dibagikan kepada semua orang (economy of sharing) yang lapar sampai mereka semua menjadi kenyang. Tindakan Yesus ini turut membuat-Nya menderita di kayu salib.[5]
Pikul salib itu memang ciri Kristen sebab Kristus dan karya-Nya menentang kejahatan manusia akibat kuasa dosa dalam bentuk ketidakadilan, keserakahan dan penindasan yang berdampak buruk bagi sesama manusia dan ciptaan lain. Setiap kali orang Kristen berhadapan dengan kejahatan itu, mereka harus menyatakan iman kepada Kristus sebagai pengikut-Nya dengan menentang kejahatan itu. Penderitaan bisa saja menjadi konsekuensi dari sikap iman itu.
Jika demikian adanya, menjadi pengikut Kristus berarti berkomitmen untuk melakukan kehendak Allah, walaupun konsekuensinya adalah penderitaan. Tentu, ini sama sekali tidak selalu diartikan sebagai menderita seperti Yesus di salib atau glorifikasi penderitaan.[6] Tetapi, dalam realitas kuasa yang melawan kehendak Allah, ada harga yang harus dibayar dalam komitmen untuk melakukan kehendak Allah. Tentu saja ada banyak hal yang membuat orang Kristen menderita dan itu akan menentukan bentuk penderitaan-Nya. Para pengikut Kristus pada masa gereja mula-mula harus menderita penganiayaan. Seorang Kristen masa kini akan menderita karena berkata jujur ketika sikap itu membuatnya dijauhi kawan-kawannya. Atau, harga yang harus dibayar itu bukan dalam pengertian penderitaan, tetapi sesuatu yang ribet atau repot tetapi sesuai kehendak Allah ketika ada hal yang praktis namun melawan kehendak Allah.
Jadi, pikul salib itu bukanlah hidup yang praktis dalam pengertian mudah dan tidak mau repot. Menjadi pengikut Yesus dalam cruciformitu ribet dan rumit. Itulah sebabnya, kehidupan para pengikut Yesus tidak bisa digerakkan oleh aspek praktis saja. Yang praktis itu memudahkan, dan itu baik. Tetapi, hidup Kristen tidak selalu ditentukan oleh apa yang memudahkan, apalagi yang praktis itu bisa jadi merupakan sikap egois manusia. Memang, hal yang praktis biasanya keluar dari teknologi sebagai daya cipta manusia yang dianugerahkan Allah. Tetapi, daya cipta itu tidak bisa dimanfaatkan sambil merusak kehidupan yang diciptakan Allah.
Kalau begitu, bagaimana kemudian kita memahami dan mewujudkan pikul salib dalam menghadapi krisis ekologis?
Pikul Salib di Tengah Krisis Ekologis
Krisis ekologis memang tidak mudah untuk diatasi, tetapi itu adalah panggilan sebagai murid Kristus – salib yang harus dipikul setiap hari. Salib ekologis ini memang beragam, mulai dari yang dilakukan gereja sebagai institusi maupun sebagai orang dalam persekutuan. Menyampaikan suara kenabian yang menentang eksploitasi tanah, pengrusakan laut, dan ketidak-adilan iklim dst. dengan segala risikonya, serta memberi solusi terhadap tata kelola sampah atau komitmen ruang kebaktian tanpa bunga plastik itu adalah salib gereja sebagai lembaga. Tetapi, tindakan-tindakan seperti menanam pohon, merawat bakau, mengelola sampah dengan baik, serta mengurangi penggunaan bahan plastik dst. itu adalah salib setiap anggota jemaat yang dilakukan secara bersama-sama sebagai satu persekutuan.
Dalam banyak hal, komitmen gereja dan jemaat terhadap tanggung jawab ekologis memang merupakan sebuah keharusan. Misalnya, ketika gereja bersepakat untuk mengurangi sampah plastik dengan tidak menyediakan air kemasan dalam berbagai acara, hal itu memang akan menjadi proses yang lebih rumit. Gereja harus menyediakan air dalam wadah besar dan menyiapkan gelas. Anggota jemaat perlu membawa botol air atau gelas dari rumah. Mereka mungkin harus mengambil air sendiri. Panitia pun harus bekerja lebih untuk mencuci gelas. Semua itu jelas merepotkan.
Namun, itulah salib yang harus dipikul, meskipun urusannya terasa ribet atau ada ketidaknyamanan yang harus ditanggung. Lagi pula, salib itu baru berupa membawa botol air atau gelas, dan sedikit usaha ekstra untuk mencucinya. Konsekuensi dari salib itu pun masih sangat ringan: tas yang dibawa ke gereja menjadi sedikit lebih berat, atau tampilan kita mungkin tidak begitu “bagus” karena tangan kanan memegang Alkitab dan tangan kiri memegang gelas.
Salibnya hanya berupa gelas atau botol air; konsekuensinya hanya sedikit berat, sedikit merepotkan, atau hanya mendengar komentar orang yang melihat tangan kita penuh dan berkata, “Beta lihat lu sa, beta rasa ribet.” Kalau hanya itu salibnya, masa kita tidak bisa memikulnya?
Jika demikian, reuse, recycle, reduce ditambah dengan replaceseharusnya menjadi salib setiap orang percaya. Narasi “ribet” untuk kebaikan dan pembaruan alam ciptaan Allah harus menjadi narasi iman. Pertanyaan “untuk apa ribet kalau ada yang praktis?” harus ditinggalkan jika itu berujung pada kerusakan alam ciptaan Allah. Yang perlu dijadikan narasi orang percaya adalah “daripada praktis tapi merusak, lebih baik ribet tapi menghidupkan.”
Narasi ribet yang demikian akan membuat orang percaya memikul salib ekologis dengan riang gembira. Tindakan itu sejalan dengan apa yang Allah lakukan dalam karya-Nya menciptakan dan memelihara ciptaan-Nya (Mzm. 104) sebagaimana dikatakan Ira D. Mangililo.[7] Setiap tindakan merawat alam, se-ribet apa pun itu, akan membawa orang percaya ke dalam pengalaman akan kegembiraan Allah dalam menciptakan dan memelihara, serta membarui ciptaan-Nya.
Jadi, barangsiapa yang hendak mengikut Yesus, ia harus memikul salib ekologis, tentu dengan riang gembira. ***
(Penulis adalah Vikaris GMIT di Jemaat Emaus Liliba dan Dosen Pascasarjana UKAW)
[1] Peter Manley Scott, “God’s Work through the Emergence of Humanity,” in T&T Clark Handbook of Christian Theology and Climate Change (London: T&T Clark, 2019), 374.
[2] Niels Henrik Gregersen. “Deep incarnation: Why evolutionary continuity matters in Christology.” Toronto Journal of Theology26, no. 2 (2010): 173-188.
[3] “Sallie McFague, “An Ecological Christology: Does Christianity Have It?” dalam Christianity and Ecology: Seeking the Well-Being of Earth and Humans(Cambridge: Harvard University Press, 2000), 41.
[4] Raj Nadella. “The Two Banquets: Mark’s Vision of Anti-Imperial Economics.” Interpretation
70, no. 2 (2016), 172-174.
[5] Bnd. Michael E. Lee. “Historical Crucifixion: A Liberationist Response to Deep Incarnation.” Theological Studies 81, no. 4 (2020), 905-907.
[6] Ini diingatkan Timothy A. Middleton dalam tulisannya, “Christic Witnessing: A Practical Response to Ecological Trauma.” Practical Theology 15, no. 5 (2022), 423. Senadi dengan itu, Daniel L. Brunner, Jennifer L. Butler, dan A. J. Swoboda juga menegaskan bahwa cruciform itu bukan hidup yang menderita karena dipaksa atau disakiti, melainkan pilihan untuk melayani dengan hati yang bebas. Yesus memberi contoh bahwa kita tidak diminta untuk menerima penderitaan yang tidak masuk akal atau yang merusak hidup. Sebaliknya, kita diajak untuk bertindak melawan penderitaan yang tidak adil dan membawa kebaikan bagi sesama ciptaan. Introducing evangelical ecotheology: Foundations in scripture, theology, history, and praxis. Baker Academic, 2014, e-Book, bab 5, bagian The Humanity of Jesus.
[7] Ira D. Mangililo. “Allah, Manusia dan Alam Semesta sebagai Satu Tubuh: Suatu Kajian Teologis terhadap Mazmur 104:1-35 dalam hubungannya dengan Peran Manusia dalam Memelihara dan Melestarikan Lingkungan Hidup” dalam Spiritualitas Ekoteologi Kristen Kontekstual(Jakarta: BPK Gunung Mulia), 117.